Jumat, 25 Desember 2009
Waktu berlalu sebagaimana seharusnya ia berlalu. Demikian juga kehidupan manusia. Bergulir, lambat tetapi pasti, penuh hasrat dan pengalaman sarat. Kehidupan macam apa? Kehidupan yang diabaikan dunia, kehidupan yang diremehkan masyarakat, kehidupan yang luput dari pengawasan nilai moral. Kehidupan anak jalanan. Atau setidaknya itulah frase yang paling mudah ditangkap bagi para pendengar awam. Karena ‘jalanan’ yang saya maksudkan di sini lebih dari sekedar perempatan atau pertigaan lalu lintas. Jalanan yang di dalamnya merupakan saksi bisu kehidupan, juga kawan dan lawan bagi anak-anak yang mengais rejeki di dalam hitamnya keadaan.
Senin, 8 Februari 2009, saya berangkat mengemban tugas live in sosial di sanggar akar, suatu tempat yang merupakan sanggar penampungan bagi anak-anak jalanan. Adapun tempat ini adalah satu dari tiga tempat yang ditawarkan kepada kami. Seminaris kelas dua Seminari Wacana Bhakti berangkat dengan sebuah visi: melihat realitas. Juga mereka yang ditempatkan si Panti Asuhan Desa Putra dan Sanggar Rebung pastilah berpikir demikian. Saya, Saudara Iman dan Saudara Eno, menuju Sanggar Akar, tempat yang mereka bilang penuh pengalaman dan hal menarik dari sebuah realita.
Kira-kira sekitar pukul sebelas kami tiba di sana. Bangunan itu bentunya tidak mencolok, sebuah rumah besar bertingkat yang dibangin dari batu bata, tetapi tidak dilapisi lagi oleh lapisan semen pada temboknya. Jadi terkesan tidak maksimal dibangun. Minimalis. Saya kira yang mereka membangunnya lebih mengutamakan adanya atap dan ruangan yang fungsional. Soal tekstur dan lapisan tembok sepertinya tidak terlalu penting. Yang lucu adalah patung lebah besar yang ada di depan bangunan. Sepertinya ada makna tersendiri, tetapi saya tidak sempat tanya. Barangkali merefleksikan kerajinan dan ketekunan seekor lebah atau semacamnya.
Tanpa basa-basi kami hubungi contact person yang sudah disebutkan, Mas Arip. Dan olehnya kami diantarkan menuju kamar transisi yang akan kami pinjam empat hari ke depan. Di kamar itu kami dipersilakan beristirahat sembari menunggu pakde datang.
Pakde itu sebenarnya pria bernama Susilo siapa gitu. Hanya saja orang di sana akrab memanggilnya Pakde. Boleh dibilang ia ini adalah rektor sanggar akar. Dia dan para staff lainnya yang menjadi juru kemudi Sangar Akar.
Kami bertemu dengannya seusai makan siang. Lucunya ia malah tidak tahu maksud kedatangan kami. Wah, ada miskomunikasi rupanya. Setelah dijelaskan, ia setuju menampung kami di sana. Bahkan kami diizinkan mengamen atau memulung. Satu pesannya yang sangat menyentuh saya. “Jadilah imam yang tidak berjarak dengan realitas itu sendiri.” Menurut Pakde, ia tidak ingin live in ini menjadi sekedar live in saja, melainkan kami harus bisa menjadi imam yang paham sungguh situasi anak-anak ini. Kami haruslah tidak berjarak dengan realitas. Kami akan dan harus menyentuh realitas itu sendiri. Demikian saya bergumam dalam hati.
Inti dari hari pertama ini ada pada pribadi satu orang bernama Desboy. Yah, memang bukan nama sebenarnya sih. Ia bilang nama ini asli. Asli karangannya. Sebenarnya ia bernama Desi, tetapi karena ada dua Desi di sana, namanya kini berjulukan Desboy. Dan hal-hal yang ia ceritakan adalah pembukaan pada hari pertama ini.
Sekiranya malam pertama kami di sana telah diberikan ‘pengantar’ yang tidak biasa oleh Desboy. Ia bercerita pertama-tama mengenai latar belakangnya. Ia berasal dari keluarga dengan enam orang anak. Tinggal di daerah Tanah Merah, Plumpang. Masa kecilnya keras, dengan kehadiran orang tua yang meski sebenarnya baik, tetapi sangat ringan tangan menurut ceritanya. Kakak sulungnya adalah seorang puteri yang membawa nama baik keluarga. Pandai di sekolah dan memboyong banyak beasiswa yang menghantarkannya hingga selesai kuliah, meski keadaan rumah tangga kurang mapan. Namun sayang kehamilannya di luar nikah telah meredupkan bintang kehidupannya. Sejak saat itu kehidupan sang kakak harus puas sebagai ibu rumah tangga dari pemuda yang tidak jelas hidupnya, menurut Desboy. Dampak pada keluarga mereka, adalah diberlakukannya kembali peham lama bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, mereka hanya akan kembali ke dapur.
Muak dengan keadaan, Desboy lari dari rumah dan mulai merangkul kerasnya jalanan sebagai sahabatnya. Ia tingal di jalanan, bertahan hidup dengan mengamen, mencopet, mencuri besi bahkan tejun ke dalam perkelahian bila perlu. Dalam hal ini sikap ‘tomboy’ yang ada padanya membuatnya menjadi tahan banting dan disegani di antara para lelaki. Bahkan jalanan telah mengahntarkannya keluar-masuk lembaga-lembaga penampungan anak-anak jalanan. Keadaan ini berlangsung beberapa lama sampai ia menemukan Sanggar Akar sebagai rumahnya yang baru pada tahun 2004.
Seusai bercerita, ia mengantarkan kami pergi berkeliling daerah itu. Sembari mengantarkan kami ia bercerita banyak mengenai kehidupan anak-anak jalanan. Ada di antara mereka yang hancur dipukuli saat mencuri besi, ada yang tewas terlindas truk dan lain sebagainya. Saya tanyakan padanya perihal kehidupan agamanya. “Itu cuma KTP doang.” Saya terenyak. Tuhan seolah tidak mereka rasakan. Masuk akal kalau melihat hidup keras yang mereka jalani, di mana dunia memalingkan muka terhadap mereka. tapi apa benar demikian? Kami berjalan kembali dan Desboy melanjutkan cerita. Kami melewati beberapa anak yang kerah bajunya ditarik ke hidung mereka. “Mereka itu lagi pada ngelem. Yang ngajarin ya yang besar-besar.” Jadi menurut Desboy, ia telah membangun sebuah basis untuk menolong anak-anak jalanan di sebuah kontarakan bersama teman-teman (waktu itu) seminaris Wacana Bhakti angkatan 18. namun seiring berjalannya waktu anak-anak jalanan yang lebih tua mengambil alih atas yang muda, lalu kemudian menguasai kontrakan itu. Hal ini juga dipengaruhi dari teman-teman seminaris yang akhirnya tidak bisa mengurus karena terfokus pada sekolah. Jadi beginilah akhirnya, anak jalanan yang lebih tua mengajarkan yang tidak-tidak dan menyiksa yang lebih muda dengan menyuruhnya mengamen dan memberikan setoran. Ironis.
Satu hal lagi yang saya renungkan dari kata-kata Desboy. Ia bilang,”Coba, berapa banyak lembaga yang menampung anak jalanan di Jakarta? Ratusan. Tapi berapa banyak anak jalanan yang masih ada di jalanan?” Jadi ia menuturkan banyak dari lembaga-lembaga tersebut yang bukannya mendidik, melainkan menyiksa dan mengkarantina anak-anak tesebut secara tidak manusiawi. Lembaga-lembaga tersebut biasanya milik pemerintah. Desboy yang telah banyak keluar masuk lembaga-lembaga tersebut, telah merasakan banyak hal. Di antaranya dikurung di dalam sel selama tiga bulan tanpa pembalut. Maka jadilah darah berceceran di mana-mana tanpa dipedulikan. Sekeluarnya dari sana, ia mencoba protes pada pemerintah, namun tetap saja tidak digubris.
Setelah itu, kami kembali ke sanggar. Saya berbaring di kamar kecil tersebut, mencoba mencerna lebih dalam apa yang dikatakan Desboy dalam benak saya. Dan pelukan kegelapan dalam balutan keheningan menghantar saya tidur.
Hari kedua. Saya bangun dan segera saja saya sadar kalau saya tidak berada di seminari. Oh iya, Desboy bilang ia akan mengantarkan kami mengamen hari ini. Maka saya sarapan bersama-sama teman-teman, baik para penghuni sanggar maupun para teman seminaris.
Sarapan mereka mencakup mie instant yang dimasak banyak-banyak. Masuk akal melihat situasinya, ada yang harus cepat pergi sekolah maupun melakukan hal lainnya. Tetapi ada satu hal mengganggu saya. Saat sarapan kami melihat sebuah guyonan. Sekelompok remaja yang lebih tua bercanda dengan bocah kecil, yang belakangan saya ketahui namanya Leman. Bercanda sih, tapi kemudian mereka menangkap anak itu beramai-ramai dan memasukkan kepalanya ke kolam lele. Saya sendiri tidak tanggap keadaan, tahu-tahu situasi yang tadinya penuh tawa (remaja yang lebih tua) dipecahkan jerit tangis kesakitan dan kemarahan Leman. Respon saya terlambat. Karena tahu-tahu anak itu sudah diblebepin begitu, saya hanya termanggu. Saya lakukan itu sebagian karena saya tahu diri sebagai orang baru dan sebagian lagi karena saya tidak tahu mau berbuat apa.
Melihat hal yang demikian saya jelas sadar kalau taraf bercanda yang mereka lakukan jelas berbeda dengan remaja umumnya (paling tidak remaja yang saya ketahui). Saya jadi ingat semalam, bahwa setiap anak jalanan telah melalui hari-hari yang tidak mudah untuk mencapai segala hal ini. Jadi kalau bercanda seperti itu mungkin harus dimaklumi dari sisi tertentu. Tunggu sebentar, dimaklumi? Tidak, itu bukan istilah yang tepat. Bukan memaklumi, tetapi seharusnya anggapan yang timbul adalah kita tidak bisa terlalu menyalahkan mereka. Kalau salah, hal itu sudah jelas salah. Tipis memang bedanya, tapi mau apa lagi? Toh belakangan, saya melihat kalau perselisihan tidak jarang tejadi di antara mereka.
Sesudah sarapan, tugas pertama kami disampaikan. Kami diminta membantu mengajar IPS Geografi untuk komnitas sanggar yang usianya setingkat anak SMP. Padahal sih, yang berusia lebih dari itu juga tidak sedikit. Dalam hal ini kami cukup tanggap keadaan dan sebisa mungkin memberikan materi yang sebisa mungkin dapat mereka cerna. Dari sini kami pun belajar bahwa bagi beberapa anak, pendidikan adalah sesuatu yang terlampau mewah. Di antara mereka sendiri, banyak terjadi pertikaian. Namun di hadapan kami, terkesan hormat dan sedikit sopan. Saya cenderung berpikir kalau mereka menganggap kami berpendidikan lebih tinggi dan maka dari itu memandang kami cukup hormat. Kelihatan dari sikap mereka saat kami mengajar. Atau mungkin juga itu supaya kami tidak masuk terlalu dalam pada situasi yang sesungguhnya dan berusaha sedapat mungkin agar sisi negatif mereka tidak menonjol?
Langsung saja deh, hari berubah menjadi siang, memaksa kami ancang-ancang untuk mengamen seperti yang kemarin sudah dibahas Desboy. Seperti janji kegiatan itu akan dilakukan seusai makan siang yang (lagi-lagi) dibumbui pertikaian ‘kecil’. “Jadi lu maunya apa?”kata Desboy. “Mau (maaf) ngewek!” Usut punya usut, Desboy yang merasa bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa Leman (yang notabene ternyata tetangganya) menanyakan hal ikhwal pertikaian tadi pagi. Tapi sepertinya tanggapan yang bersahabat dan rasional itu sesuatu yang cenderung mahal dalam hal-hal tertentu dalam pergaulan mereka.
Oke, tanpa basa-basi akhirnya kami berangkat setelah semuanya siap Desboy, Leman, Iman, Eno juga saya siap melihat kejamnya dunia. Eng? Leman? Ah, sebenarnya karena kasus tadi pagi ia (lagi-lagi menurut Desboy) sebaiknya pulang dahulu ke rumahnya karena teman-teman yang melakukan hal tersebut akan diusut. Jadi Leman sebaiknya pulang untuk menghindari perselisihan yang bukan tak mungkin terjadi lagi. Maka jadilah Leman ikut menemani pembelajaran kami.
Langsung saja, singkat cerita kegiatan kami hari ini adalah mengamen. Satu hal yang saya tangkap adalah mengenai identitas saya. Jelas, sekarang saya bukan lagi seminaris hanya ingin melihat-lihat kehidupan, melainkan kini saya sungguh menjadi bagian dari kerasnya jalanan. Seseorang yang berdiri di antara raungan diesel dan jeritan kabut asap kendaraan untuk bertahan, itulah saya. Saya tahu benar peran saya di sini, maka saya tidak mengalami krisis identitas atau menderita rasa malu yang tidak perlu saat mengamen. Itu semua hal yang tidak perlu. Rasionalisasi dan harga diri yang tidak pada tempatnya tidak dibutuhkan di tempat ini.
Mulanya kami ‘berlatih’ di perempatan. Yang pertama berkelompok, lantas sendiri-sendiri. Lumayan mendapat kepuasan di sana, maka dilanjutkan di dalam bus. Kendaraan diesel itu mengantar kami ke suatu tempat bernama Plumpang.
Plumpang adalah suatu kawasan di mana terdapat tanki-tanki BBM milik Pertamina. Atau setidaknya, itulah pendapat orang banyak. Tapi bagi anak jalanan, inilah daerah yang sangat buas, dihuni gerombolan preman dan anak-anak jalanan lain yang berwatak keras. Kekerasan tentu bukan barang baru bagi mereka. Sudah jamak terjadi adu jotos untuk klimaks ‘penyelesaian’ masalah. Dan di tempat yang bengis inilah, Desboy tumbuh. Tak heran masa lalunya menyimpan banyak cerita, pikir saya.
Kami masuk ke daerah itu. Pelosok daerah itu bernama Tanah Merah. Saya memperhatikan sekitar. Di sekeliling saya berdiri perumahan kumuh yang becek dan bau amis karena tergenang banjir. Rata-rata orang kenal Desboy. Sanbil berjalan, cerita pun meluncur lagi dari mulutnya. Perihal hidup dan masa-masa yang telah ia lewati di tempat ini dijabarkannya kepada kami.
Pertama-tama, kami pergi ke rumah Leman. Walau hanya sebentar di rumah kayu kecil itu, banyak hal yang bisa diambil darinya. Dari apa yang dikatakannya, tempat yang mereka tinggali itu dihuni oleh 16.000 orang. Semuanya, adalah orang-orang kecil yang tentunya tidak punya rumah dan akhirnya bermukin di sana. Daerah ini sangat rawan bila terjadi apa-apa dengan tanki-tanki BBM tersebut. Pasalnya, letaknya persis di belakang tempat tersebut. Musibah meledaknya tanki tempo hari pun betul-betul mujur bagi mereka, karena api tidak sampai ke daerah itu.
Ayah Leman yang berprofesi sebagai pemulung itu agaknya reflektif juga. Ia berkata,”Gak perlu jadi orang baik, belajar baik dulu aja dah. Kalau jadi orang baik, sedikit-sedikit minta maaf. Itu aja udah salah ‘kan? Orang sekarang mikirnya udah sampe ke planet-planet. Kalau saya di bumi dulu aja dah.” Dari kata-katanya, saya dapat menangkap, kalau ia mengharapkan yang terbaik bagi anak-anaknya, namun tidak perlu yang muluk-muluk. Ia terlihat lebih tenggelam pada bagaimana mengurus hidup bagi anak-anaknya agar bisa terus bertahan, tanpa terlalu tinggi berkhayal.
Kunjungan berikutnya adalah tumah Desboy. Di rumah kayu yang mungil itu ternyata sarat pengalaman dan refleksi kehidupan.kami menyimak dengan seksama pengalaman-pengalaman yang telah menimpa mereka. Bagaimana dahulu mereka pernah tertipu undian palsu, terkena musibah kebakaran juga hal-hal lain yang menimpa mereka, kami dengarkan dengan seksama. Sungguh hidup mereka mengandun hal-hal yang mungkin tidak akan pernah kita pikirkan, namun inilah realita. Dan Tuhan ada di dalam realita, bukan khayalan kosong dalam gemerlapnya dunia.
Bahkan saat pulang pun kami masih sempat menyaksikan pemukulan dan perkelahian terhadap seorang anak di jalanan, yang ternyata kurang membayar setoran pada ‘petingginya’. Melihat hal itu, Desboy yang peka meminta hasil mengamen kami dan memberikannya padanya. Ia pun juga mencoba bertindak selaku penengah masalah itu. Dan kami pun kembali ke sanggar akar, setelah satu kali mengamen, meski ada insiden kecil yang membuat kami terpisah dengan Desboy.
Hari berikutnya dengan rencana berikutnya. Agenda kami hari ini: memulung. Dan sebelum itu:mengajar. Bahannya ilmu pengetahuan alam bagi siswa sanggar yang setingkat murid SD. Kami mempersiapkan hati dan tenaga untuk bersiap menghadapi hari ini. Tapi soal memulung itu kami harus menunggu, karena Desboy harus sekolah terlebih dahulu.
Pada siang harinya, Desboy sudah kembali ke sanggar. Kali ini kami akan ditemani seseorang untuk mengamen di bus dalam perjalanan (lagi-lagi) ke Plumpang. Nama orang itu Johan. Jadi supaya kami tidak membayar terlalu banyak di bus, ada yang jadi pengamen dan ada yang jadi penumpang. Sama seperti kemarin.
Di daerah yang sama, kami kembali berpetualang mencari kenalan Desboy yang memiliki gerobak sekaligus kait yang digunakan untuk memulung, yang mereka sebut gancu. Setelah gerobak didapatkan, izin pun diberikan pula. Maka jkami berpetualang menyisir jalan mencari apapun yang laku untuk dijual. Barang-barang tersebut bisa saja kardus, botol air mineral, botol plastik dan lainnya.
Kami menyisir jalan dengan membawa gerobak bergantian. Pembagian tugas pun dilakukan, yaitu satu orang berada bersama pembawa gerobak, dan yang satu berjalan di sisi lain jalan dengan karung dan gancu. Semua itu kami lakukan dengan hati besar, berusaha menyelami realita sosial yang ada, guna mencetak pribadi kami dan membuka jendela hati terhadap hitamnya keadaan anak-anak ibukota.
Dan jadilah petualangan ini kami lakukan di bawah rintik-rintik hujan. Keluar masuk pasar dan menyusuri jalan-jalan raya, kami menjadi manusia yang lain. Manusia-manusia yang ingin mencari uang untuk kehidupan dengan menggantungkan harapan pada gancu dan karung. Dan manusia-manusia ini pun tak jarang juga bertemu orang-orang yang senasib sepenanggungan. Banyak pemulung-pemulung di jalan itu dan kami terus berjalan sambil berefleksi di dalam hati. Di manakah Tuhan bagi para pemulung? Tuhan hadir di dalam botol-botol plastik dan kardus yang ada di hadapan mereka. Tuhan hadir dalam angka timbangan yang menunjukkan beratnya sampah yang mereka kumpulkan. Dan Tuhan senantiasa hadir dalam kekuatan dan ketahanan mereka melewati keadaan dan cemoohan orang, yang juga oleh kami telah dirasakan.
Seselesainya kami dari sana, perolehan kami harus ditimbang. Ternyata, kerja keras kami dari siang hingga sore dihargai enam ribu rupiah! Di dalam hati saya, saya berpikir kalau nominal tersebut jauh di bawah pendapatan mengamen kami tempo hari. Namun sekali lagi, saya berhadapan dengan realita. Pahitnya keadaan hanya bisa dikalahkan dengan kerja keras. Dan bila hal itu sudah terwujud kekuatan kita akan bersanding dengan pahitnya keadaan sebagai teman yang saling menerima dan memberi, baik itu marabahaya maupun rejeki.
Sementara senja menghitam, kami sempat menikmati keramahan dari keluarga Desboy di Tanah Merah. Sepiring ubi goreng dan susu hangat ternyata adalah teman yang menyenangkan dalam pembicaraan kami sore itu. dan salah satu pembicaraan yang saya dengar, ternyata mereka harus membayar sesuatu bagi sekolah Desboy perihal ujian akhir dan hal tersebut jumlahnya tidak sedikit. Tapi kalau saya tidak salah dengar, Desboy mengatakan kalau sudah diselesaikan ia ‘pasti lulus’. Maksudnya apa silakan dipikirkan sendiri.
Saya tersentuh dengan kehidupan mereka, yang oleh orang-orang mapan pastilah merupakan suatu kejijikan ternyata berkilau seperti mutiara. Cahaya kilauan itu membuat saya sadar, mereka pun citraan Allah. Tetapi bedanya mereka citraan Allah yang tumbuh di tengah-tengah kejamnya dunia. Dan kebaikan mereka sore itu membuka mata saya bahwa orang-orang yang mapan hidupnya pun tidaklah lebih tinggi dari mereka. Semua manusia sama berharga dan setara derajatnya. Dinding kekayaan tidaklah cukup tegar untuk membedakan manusia, sebab Allah tetap hadir di dalam diri manusia itu, apapun keadaannya. Hanya masalahnya, apakah kita cukup rendah hati untuk mendengarkan-Nya? Dan kami pun kembali ke sanggar membawa pelbagai pemikiran perihal dunia ini.
Malamnya, kami bertiga berbaring sembari memikirkan dan memperbincangkan hal-hal yang telah kami peroleh sepanjang hari itu. Saya sendiri mendapat sedikit masalah dengan perut saya, barangkali karena hujan, saya terkena diare yang cukup merepotkan. Dan malam itu itu Desboy, untuk yang terakhir kalinya masuk dan berbicara kapada kami. Ia mengatakan banyak hal malam itu. Ia berharap kunjungan kami ke sini tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi selalu membekas di hati kami agar kehidupan yang anak jalanan yang telah kami lalui tidaklah sirna begitu saja, melainkan Sanggar Akar dan semua yang ada di dalamnya menjadi kenangan dan pembelajaran yang berharga.
Ia juga sempat bercerita lagi tentang kerasnya kehidupan yang ia jalani sebagai kuli bangunan dan sempat ditipu mandornya. Juga ada cerita saat ia hendak diadopsi seorang kaya tetapi tak tahan karena tak mau disekolahkan dan belajar bahasa Jerman. Semua pahit manis kenangan tersebut ia bagikan tanpa rasa sungkan, membuat hati kami semakin tersentuh dan dekat dengannya. Terakhir, ia menitipkan surat untuk para sahabatnya di Gonzaga, dan sebuah kamera pemberian salah seorang sahabat lamanya. “Tolong diliat. Masih bener apa enggak, gua nggak tahu. Gua nggak punya batere, belinya mahal.” Maka jadilah kamera tersebut kami bawa untuk dilihat apakah bermasalah atau tidak. Ia juga menyertakan permintaan maaf apabila ia atau teman-teman sanggar yang lain berbuat salah terhadap kami. Dan tanpa terasa, selesailah perbincangan kami.
Kami bangun keesokan harinya dan berkata di dalam hati, “Sudah berakhir ya…?” Kemudian sarapan di tempat itu untuk terakhir kalinya, dan tak berapa lama kemudian, siap berangkat. Maka, seusai berpamitan pada para pengajar dan penghuni sanggar, kami melewati gerbang itu membawa harapan untuk bisa kembali lagi ke sana, menepati janji pada Desboy yang tidak akan kami tidak melupakannya. Dan di luar gerbang itu, Tuhan yang mengajar dan menyertai kami dalam pembelajaran hidup kami di Sanggar Akar, sudah menunggu kami di tempat lain, Seminari Wacana Bhakti.
Senin, 8 Februari 2009, saya berangkat mengemban tugas live in sosial di sanggar akar, suatu tempat yang merupakan sanggar penampungan bagi anak-anak jalanan. Adapun tempat ini adalah satu dari tiga tempat yang ditawarkan kepada kami. Seminaris kelas dua Seminari Wacana Bhakti berangkat dengan sebuah visi: melihat realitas. Juga mereka yang ditempatkan si Panti Asuhan Desa Putra dan Sanggar Rebung pastilah berpikir demikian. Saya, Saudara Iman dan Saudara Eno, menuju Sanggar Akar, tempat yang mereka bilang penuh pengalaman dan hal menarik dari sebuah realita.
Kira-kira sekitar pukul sebelas kami tiba di sana. Bangunan itu bentunya tidak mencolok, sebuah rumah besar bertingkat yang dibangin dari batu bata, tetapi tidak dilapisi lagi oleh lapisan semen pada temboknya. Jadi terkesan tidak maksimal dibangun. Minimalis. Saya kira yang mereka membangunnya lebih mengutamakan adanya atap dan ruangan yang fungsional. Soal tekstur dan lapisan tembok sepertinya tidak terlalu penting. Yang lucu adalah patung lebah besar yang ada di depan bangunan. Sepertinya ada makna tersendiri, tetapi saya tidak sempat tanya. Barangkali merefleksikan kerajinan dan ketekunan seekor lebah atau semacamnya.
Tanpa basa-basi kami hubungi contact person yang sudah disebutkan, Mas Arip. Dan olehnya kami diantarkan menuju kamar transisi yang akan kami pinjam empat hari ke depan. Di kamar itu kami dipersilakan beristirahat sembari menunggu pakde datang.
Pakde itu sebenarnya pria bernama Susilo siapa gitu. Hanya saja orang di sana akrab memanggilnya Pakde. Boleh dibilang ia ini adalah rektor sanggar akar. Dia dan para staff lainnya yang menjadi juru kemudi Sangar Akar.
Kami bertemu dengannya seusai makan siang. Lucunya ia malah tidak tahu maksud kedatangan kami. Wah, ada miskomunikasi rupanya. Setelah dijelaskan, ia setuju menampung kami di sana. Bahkan kami diizinkan mengamen atau memulung. Satu pesannya yang sangat menyentuh saya. “Jadilah imam yang tidak berjarak dengan realitas itu sendiri.” Menurut Pakde, ia tidak ingin live in ini menjadi sekedar live in saja, melainkan kami harus bisa menjadi imam yang paham sungguh situasi anak-anak ini. Kami haruslah tidak berjarak dengan realitas. Kami akan dan harus menyentuh realitas itu sendiri. Demikian saya bergumam dalam hati.
Inti dari hari pertama ini ada pada pribadi satu orang bernama Desboy. Yah, memang bukan nama sebenarnya sih. Ia bilang nama ini asli. Asli karangannya. Sebenarnya ia bernama Desi, tetapi karena ada dua Desi di sana, namanya kini berjulukan Desboy. Dan hal-hal yang ia ceritakan adalah pembukaan pada hari pertama ini.
Sekiranya malam pertama kami di sana telah diberikan ‘pengantar’ yang tidak biasa oleh Desboy. Ia bercerita pertama-tama mengenai latar belakangnya. Ia berasal dari keluarga dengan enam orang anak. Tinggal di daerah Tanah Merah, Plumpang. Masa kecilnya keras, dengan kehadiran orang tua yang meski sebenarnya baik, tetapi sangat ringan tangan menurut ceritanya. Kakak sulungnya adalah seorang puteri yang membawa nama baik keluarga. Pandai di sekolah dan memboyong banyak beasiswa yang menghantarkannya hingga selesai kuliah, meski keadaan rumah tangga kurang mapan. Namun sayang kehamilannya di luar nikah telah meredupkan bintang kehidupannya. Sejak saat itu kehidupan sang kakak harus puas sebagai ibu rumah tangga dari pemuda yang tidak jelas hidupnya, menurut Desboy. Dampak pada keluarga mereka, adalah diberlakukannya kembali peham lama bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, mereka hanya akan kembali ke dapur.
Muak dengan keadaan, Desboy lari dari rumah dan mulai merangkul kerasnya jalanan sebagai sahabatnya. Ia tingal di jalanan, bertahan hidup dengan mengamen, mencopet, mencuri besi bahkan tejun ke dalam perkelahian bila perlu. Dalam hal ini sikap ‘tomboy’ yang ada padanya membuatnya menjadi tahan banting dan disegani di antara para lelaki. Bahkan jalanan telah mengahntarkannya keluar-masuk lembaga-lembaga penampungan anak-anak jalanan. Keadaan ini berlangsung beberapa lama sampai ia menemukan Sanggar Akar sebagai rumahnya yang baru pada tahun 2004.
Seusai bercerita, ia mengantarkan kami pergi berkeliling daerah itu. Sembari mengantarkan kami ia bercerita banyak mengenai kehidupan anak-anak jalanan. Ada di antara mereka yang hancur dipukuli saat mencuri besi, ada yang tewas terlindas truk dan lain sebagainya. Saya tanyakan padanya perihal kehidupan agamanya. “Itu cuma KTP doang.” Saya terenyak. Tuhan seolah tidak mereka rasakan. Masuk akal kalau melihat hidup keras yang mereka jalani, di mana dunia memalingkan muka terhadap mereka. tapi apa benar demikian? Kami berjalan kembali dan Desboy melanjutkan cerita. Kami melewati beberapa anak yang kerah bajunya ditarik ke hidung mereka. “Mereka itu lagi pada ngelem. Yang ngajarin ya yang besar-besar.” Jadi menurut Desboy, ia telah membangun sebuah basis untuk menolong anak-anak jalanan di sebuah kontarakan bersama teman-teman (waktu itu) seminaris Wacana Bhakti angkatan 18. namun seiring berjalannya waktu anak-anak jalanan yang lebih tua mengambil alih atas yang muda, lalu kemudian menguasai kontrakan itu. Hal ini juga dipengaruhi dari teman-teman seminaris yang akhirnya tidak bisa mengurus karena terfokus pada sekolah. Jadi beginilah akhirnya, anak jalanan yang lebih tua mengajarkan yang tidak-tidak dan menyiksa yang lebih muda dengan menyuruhnya mengamen dan memberikan setoran. Ironis.
Satu hal lagi yang saya renungkan dari kata-kata Desboy. Ia bilang,”Coba, berapa banyak lembaga yang menampung anak jalanan di Jakarta? Ratusan. Tapi berapa banyak anak jalanan yang masih ada di jalanan?” Jadi ia menuturkan banyak dari lembaga-lembaga tersebut yang bukannya mendidik, melainkan menyiksa dan mengkarantina anak-anak tesebut secara tidak manusiawi. Lembaga-lembaga tersebut biasanya milik pemerintah. Desboy yang telah banyak keluar masuk lembaga-lembaga tersebut, telah merasakan banyak hal. Di antaranya dikurung di dalam sel selama tiga bulan tanpa pembalut. Maka jadilah darah berceceran di mana-mana tanpa dipedulikan. Sekeluarnya dari sana, ia mencoba protes pada pemerintah, namun tetap saja tidak digubris.
Setelah itu, kami kembali ke sanggar. Saya berbaring di kamar kecil tersebut, mencoba mencerna lebih dalam apa yang dikatakan Desboy dalam benak saya. Dan pelukan kegelapan dalam balutan keheningan menghantar saya tidur.
Hari kedua. Saya bangun dan segera saja saya sadar kalau saya tidak berada di seminari. Oh iya, Desboy bilang ia akan mengantarkan kami mengamen hari ini. Maka saya sarapan bersama-sama teman-teman, baik para penghuni sanggar maupun para teman seminaris.
Sarapan mereka mencakup mie instant yang dimasak banyak-banyak. Masuk akal melihat situasinya, ada yang harus cepat pergi sekolah maupun melakukan hal lainnya. Tetapi ada satu hal mengganggu saya. Saat sarapan kami melihat sebuah guyonan. Sekelompok remaja yang lebih tua bercanda dengan bocah kecil, yang belakangan saya ketahui namanya Leman. Bercanda sih, tapi kemudian mereka menangkap anak itu beramai-ramai dan memasukkan kepalanya ke kolam lele. Saya sendiri tidak tanggap keadaan, tahu-tahu situasi yang tadinya penuh tawa (remaja yang lebih tua) dipecahkan jerit tangis kesakitan dan kemarahan Leman. Respon saya terlambat. Karena tahu-tahu anak itu sudah diblebepin begitu, saya hanya termanggu. Saya lakukan itu sebagian karena saya tahu diri sebagai orang baru dan sebagian lagi karena saya tidak tahu mau berbuat apa.
Melihat hal yang demikian saya jelas sadar kalau taraf bercanda yang mereka lakukan jelas berbeda dengan remaja umumnya (paling tidak remaja yang saya ketahui). Saya jadi ingat semalam, bahwa setiap anak jalanan telah melalui hari-hari yang tidak mudah untuk mencapai segala hal ini. Jadi kalau bercanda seperti itu mungkin harus dimaklumi dari sisi tertentu. Tunggu sebentar, dimaklumi? Tidak, itu bukan istilah yang tepat. Bukan memaklumi, tetapi seharusnya anggapan yang timbul adalah kita tidak bisa terlalu menyalahkan mereka. Kalau salah, hal itu sudah jelas salah. Tipis memang bedanya, tapi mau apa lagi? Toh belakangan, saya melihat kalau perselisihan tidak jarang tejadi di antara mereka.
Sesudah sarapan, tugas pertama kami disampaikan. Kami diminta membantu mengajar IPS Geografi untuk komnitas sanggar yang usianya setingkat anak SMP. Padahal sih, yang berusia lebih dari itu juga tidak sedikit. Dalam hal ini kami cukup tanggap keadaan dan sebisa mungkin memberikan materi yang sebisa mungkin dapat mereka cerna. Dari sini kami pun belajar bahwa bagi beberapa anak, pendidikan adalah sesuatu yang terlampau mewah. Di antara mereka sendiri, banyak terjadi pertikaian. Namun di hadapan kami, terkesan hormat dan sedikit sopan. Saya cenderung berpikir kalau mereka menganggap kami berpendidikan lebih tinggi dan maka dari itu memandang kami cukup hormat. Kelihatan dari sikap mereka saat kami mengajar. Atau mungkin juga itu supaya kami tidak masuk terlalu dalam pada situasi yang sesungguhnya dan berusaha sedapat mungkin agar sisi negatif mereka tidak menonjol?
Langsung saja deh, hari berubah menjadi siang, memaksa kami ancang-ancang untuk mengamen seperti yang kemarin sudah dibahas Desboy. Seperti janji kegiatan itu akan dilakukan seusai makan siang yang (lagi-lagi) dibumbui pertikaian ‘kecil’. “Jadi lu maunya apa?”kata Desboy. “Mau (maaf) ngewek!” Usut punya usut, Desboy yang merasa bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa Leman (yang notabene ternyata tetangganya) menanyakan hal ikhwal pertikaian tadi pagi. Tapi sepertinya tanggapan yang bersahabat dan rasional itu sesuatu yang cenderung mahal dalam hal-hal tertentu dalam pergaulan mereka.
Oke, tanpa basa-basi akhirnya kami berangkat setelah semuanya siap Desboy, Leman, Iman, Eno juga saya siap melihat kejamnya dunia. Eng? Leman? Ah, sebenarnya karena kasus tadi pagi ia (lagi-lagi menurut Desboy) sebaiknya pulang dahulu ke rumahnya karena teman-teman yang melakukan hal tersebut akan diusut. Jadi Leman sebaiknya pulang untuk menghindari perselisihan yang bukan tak mungkin terjadi lagi. Maka jadilah Leman ikut menemani pembelajaran kami.
Langsung saja, singkat cerita kegiatan kami hari ini adalah mengamen. Satu hal yang saya tangkap adalah mengenai identitas saya. Jelas, sekarang saya bukan lagi seminaris hanya ingin melihat-lihat kehidupan, melainkan kini saya sungguh menjadi bagian dari kerasnya jalanan. Seseorang yang berdiri di antara raungan diesel dan jeritan kabut asap kendaraan untuk bertahan, itulah saya. Saya tahu benar peran saya di sini, maka saya tidak mengalami krisis identitas atau menderita rasa malu yang tidak perlu saat mengamen. Itu semua hal yang tidak perlu. Rasionalisasi dan harga diri yang tidak pada tempatnya tidak dibutuhkan di tempat ini.
Mulanya kami ‘berlatih’ di perempatan. Yang pertama berkelompok, lantas sendiri-sendiri. Lumayan mendapat kepuasan di sana, maka dilanjutkan di dalam bus. Kendaraan diesel itu mengantar kami ke suatu tempat bernama Plumpang.
Plumpang adalah suatu kawasan di mana terdapat tanki-tanki BBM milik Pertamina. Atau setidaknya, itulah pendapat orang banyak. Tapi bagi anak jalanan, inilah daerah yang sangat buas, dihuni gerombolan preman dan anak-anak jalanan lain yang berwatak keras. Kekerasan tentu bukan barang baru bagi mereka. Sudah jamak terjadi adu jotos untuk klimaks ‘penyelesaian’ masalah. Dan di tempat yang bengis inilah, Desboy tumbuh. Tak heran masa lalunya menyimpan banyak cerita, pikir saya.
Kami masuk ke daerah itu. Pelosok daerah itu bernama Tanah Merah. Saya memperhatikan sekitar. Di sekeliling saya berdiri perumahan kumuh yang becek dan bau amis karena tergenang banjir. Rata-rata orang kenal Desboy. Sanbil berjalan, cerita pun meluncur lagi dari mulutnya. Perihal hidup dan masa-masa yang telah ia lewati di tempat ini dijabarkannya kepada kami.
Pertama-tama, kami pergi ke rumah Leman. Walau hanya sebentar di rumah kayu kecil itu, banyak hal yang bisa diambil darinya. Dari apa yang dikatakannya, tempat yang mereka tinggali itu dihuni oleh 16.000 orang. Semuanya, adalah orang-orang kecil yang tentunya tidak punya rumah dan akhirnya bermukin di sana. Daerah ini sangat rawan bila terjadi apa-apa dengan tanki-tanki BBM tersebut. Pasalnya, letaknya persis di belakang tempat tersebut. Musibah meledaknya tanki tempo hari pun betul-betul mujur bagi mereka, karena api tidak sampai ke daerah itu.
Ayah Leman yang berprofesi sebagai pemulung itu agaknya reflektif juga. Ia berkata,”Gak perlu jadi orang baik, belajar baik dulu aja dah. Kalau jadi orang baik, sedikit-sedikit minta maaf. Itu aja udah salah ‘kan? Orang sekarang mikirnya udah sampe ke planet-planet. Kalau saya di bumi dulu aja dah.” Dari kata-katanya, saya dapat menangkap, kalau ia mengharapkan yang terbaik bagi anak-anaknya, namun tidak perlu yang muluk-muluk. Ia terlihat lebih tenggelam pada bagaimana mengurus hidup bagi anak-anaknya agar bisa terus bertahan, tanpa terlalu tinggi berkhayal.
Kunjungan berikutnya adalah tumah Desboy. Di rumah kayu yang mungil itu ternyata sarat pengalaman dan refleksi kehidupan.kami menyimak dengan seksama pengalaman-pengalaman yang telah menimpa mereka. Bagaimana dahulu mereka pernah tertipu undian palsu, terkena musibah kebakaran juga hal-hal lain yang menimpa mereka, kami dengarkan dengan seksama. Sungguh hidup mereka mengandun hal-hal yang mungkin tidak akan pernah kita pikirkan, namun inilah realita. Dan Tuhan ada di dalam realita, bukan khayalan kosong dalam gemerlapnya dunia.
Bahkan saat pulang pun kami masih sempat menyaksikan pemukulan dan perkelahian terhadap seorang anak di jalanan, yang ternyata kurang membayar setoran pada ‘petingginya’. Melihat hal itu, Desboy yang peka meminta hasil mengamen kami dan memberikannya padanya. Ia pun juga mencoba bertindak selaku penengah masalah itu. Dan kami pun kembali ke sanggar akar, setelah satu kali mengamen, meski ada insiden kecil yang membuat kami terpisah dengan Desboy.
Hari berikutnya dengan rencana berikutnya. Agenda kami hari ini: memulung. Dan sebelum itu:mengajar. Bahannya ilmu pengetahuan alam bagi siswa sanggar yang setingkat murid SD. Kami mempersiapkan hati dan tenaga untuk bersiap menghadapi hari ini. Tapi soal memulung itu kami harus menunggu, karena Desboy harus sekolah terlebih dahulu.
Pada siang harinya, Desboy sudah kembali ke sanggar. Kali ini kami akan ditemani seseorang untuk mengamen di bus dalam perjalanan (lagi-lagi) ke Plumpang. Nama orang itu Johan. Jadi supaya kami tidak membayar terlalu banyak di bus, ada yang jadi pengamen dan ada yang jadi penumpang. Sama seperti kemarin.
Di daerah yang sama, kami kembali berpetualang mencari kenalan Desboy yang memiliki gerobak sekaligus kait yang digunakan untuk memulung, yang mereka sebut gancu. Setelah gerobak didapatkan, izin pun diberikan pula. Maka jkami berpetualang menyisir jalan mencari apapun yang laku untuk dijual. Barang-barang tersebut bisa saja kardus, botol air mineral, botol plastik dan lainnya.
Kami menyisir jalan dengan membawa gerobak bergantian. Pembagian tugas pun dilakukan, yaitu satu orang berada bersama pembawa gerobak, dan yang satu berjalan di sisi lain jalan dengan karung dan gancu. Semua itu kami lakukan dengan hati besar, berusaha menyelami realita sosial yang ada, guna mencetak pribadi kami dan membuka jendela hati terhadap hitamnya keadaan anak-anak ibukota.
Dan jadilah petualangan ini kami lakukan di bawah rintik-rintik hujan. Keluar masuk pasar dan menyusuri jalan-jalan raya, kami menjadi manusia yang lain. Manusia-manusia yang ingin mencari uang untuk kehidupan dengan menggantungkan harapan pada gancu dan karung. Dan manusia-manusia ini pun tak jarang juga bertemu orang-orang yang senasib sepenanggungan. Banyak pemulung-pemulung di jalan itu dan kami terus berjalan sambil berefleksi di dalam hati. Di manakah Tuhan bagi para pemulung? Tuhan hadir di dalam botol-botol plastik dan kardus yang ada di hadapan mereka. Tuhan hadir dalam angka timbangan yang menunjukkan beratnya sampah yang mereka kumpulkan. Dan Tuhan senantiasa hadir dalam kekuatan dan ketahanan mereka melewati keadaan dan cemoohan orang, yang juga oleh kami telah dirasakan.
Seselesainya kami dari sana, perolehan kami harus ditimbang. Ternyata, kerja keras kami dari siang hingga sore dihargai enam ribu rupiah! Di dalam hati saya, saya berpikir kalau nominal tersebut jauh di bawah pendapatan mengamen kami tempo hari. Namun sekali lagi, saya berhadapan dengan realita. Pahitnya keadaan hanya bisa dikalahkan dengan kerja keras. Dan bila hal itu sudah terwujud kekuatan kita akan bersanding dengan pahitnya keadaan sebagai teman yang saling menerima dan memberi, baik itu marabahaya maupun rejeki.
Sementara senja menghitam, kami sempat menikmati keramahan dari keluarga Desboy di Tanah Merah. Sepiring ubi goreng dan susu hangat ternyata adalah teman yang menyenangkan dalam pembicaraan kami sore itu. dan salah satu pembicaraan yang saya dengar, ternyata mereka harus membayar sesuatu bagi sekolah Desboy perihal ujian akhir dan hal tersebut jumlahnya tidak sedikit. Tapi kalau saya tidak salah dengar, Desboy mengatakan kalau sudah diselesaikan ia ‘pasti lulus’. Maksudnya apa silakan dipikirkan sendiri.
Saya tersentuh dengan kehidupan mereka, yang oleh orang-orang mapan pastilah merupakan suatu kejijikan ternyata berkilau seperti mutiara. Cahaya kilauan itu membuat saya sadar, mereka pun citraan Allah. Tetapi bedanya mereka citraan Allah yang tumbuh di tengah-tengah kejamnya dunia. Dan kebaikan mereka sore itu membuka mata saya bahwa orang-orang yang mapan hidupnya pun tidaklah lebih tinggi dari mereka. Semua manusia sama berharga dan setara derajatnya. Dinding kekayaan tidaklah cukup tegar untuk membedakan manusia, sebab Allah tetap hadir di dalam diri manusia itu, apapun keadaannya. Hanya masalahnya, apakah kita cukup rendah hati untuk mendengarkan-Nya? Dan kami pun kembali ke sanggar membawa pelbagai pemikiran perihal dunia ini.
Malamnya, kami bertiga berbaring sembari memikirkan dan memperbincangkan hal-hal yang telah kami peroleh sepanjang hari itu. Saya sendiri mendapat sedikit masalah dengan perut saya, barangkali karena hujan, saya terkena diare yang cukup merepotkan. Dan malam itu itu Desboy, untuk yang terakhir kalinya masuk dan berbicara kapada kami. Ia mengatakan banyak hal malam itu. Ia berharap kunjungan kami ke sini tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi selalu membekas di hati kami agar kehidupan yang anak jalanan yang telah kami lalui tidaklah sirna begitu saja, melainkan Sanggar Akar dan semua yang ada di dalamnya menjadi kenangan dan pembelajaran yang berharga.
Ia juga sempat bercerita lagi tentang kerasnya kehidupan yang ia jalani sebagai kuli bangunan dan sempat ditipu mandornya. Juga ada cerita saat ia hendak diadopsi seorang kaya tetapi tak tahan karena tak mau disekolahkan dan belajar bahasa Jerman. Semua pahit manis kenangan tersebut ia bagikan tanpa rasa sungkan, membuat hati kami semakin tersentuh dan dekat dengannya. Terakhir, ia menitipkan surat untuk para sahabatnya di Gonzaga, dan sebuah kamera pemberian salah seorang sahabat lamanya. “Tolong diliat. Masih bener apa enggak, gua nggak tahu. Gua nggak punya batere, belinya mahal.” Maka jadilah kamera tersebut kami bawa untuk dilihat apakah bermasalah atau tidak. Ia juga menyertakan permintaan maaf apabila ia atau teman-teman sanggar yang lain berbuat salah terhadap kami. Dan tanpa terasa, selesailah perbincangan kami.
Kami bangun keesokan harinya dan berkata di dalam hati, “Sudah berakhir ya…?” Kemudian sarapan di tempat itu untuk terakhir kalinya, dan tak berapa lama kemudian, siap berangkat. Maka, seusai berpamitan pada para pengajar dan penghuni sanggar, kami melewati gerbang itu membawa harapan untuk bisa kembali lagi ke sana, menepati janji pada Desboy yang tidak akan kami tidak melupakannya. Dan di luar gerbang itu, Tuhan yang mengajar dan menyertai kami dalam pembelajaran hidup kami di Sanggar Akar, sudah menunggu kami di tempat lain, Seminari Wacana Bhakti.








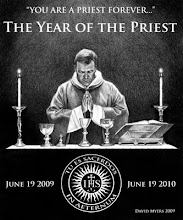




0 komentar:
Posting Komentar